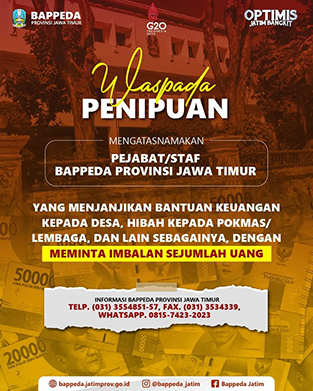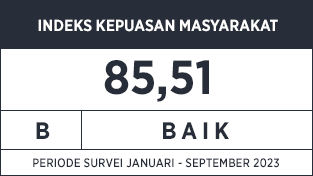Ilustrasi
Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Sejauh ini, di tingkat pusat, urusan ketahanan pangan ditangani oleh beberapa kementerian dan badan usaha milik negara. Sebagai contoh, Kementerian Pertanian, yang berupaya mengawal kebijakan produksi pangan, perkebunan, peternakan, peningkatan produktivitas, pengelolaan lahan dan air irigasi, pengolahan dan pemasaran hasil, pengembangan sumber daya manusia (melalui penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan), penelitian dan pengembangan, serta koordinasi pemantapan ketahanan pangan.
Sementara, Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab pada urusan pembinaan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota melalui koordinasi kebijakan pangan dan pertanian antardaerah otonom, pemberian insentif perwilayahan komoditas pangan, pengalokasian dana ketahanan pangan, dalam kaitannya dengan fasilitasi penyusunan anggaran daerah, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
Urusan wajib
Namun, sejak era desentralisasi pemerintahan di republik ini bergulir, urusan ketahanan pangan bukan hanya menjadi urusan pemerintah pusat, melainkan juga telah menjadi urusan wajib bagi daerah. Artinya, pemerintah daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab lebih untuk mengurus dan mengatur ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing. Tujuannya, agar potensi pangan daerah bisa tergali, sehingga bisa memperkuat ketahanan pangan di daerah.
Pemerintah pusat cukup menentukan arah kebijakan, strategi, dan sasaran yang akan dicapai menuju tingkat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sementara, pemerintah daerah wajib melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelengaraan ketahanan pangan di wilayahnya dengan memerhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Penyerahan urusan ketahanan pangan senyatanya sudah dimulai sejak terbitnya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan berlakunya PP No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Belakangan, aturan perundangan itu diganti dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Dengan aturan itu, pemerintah daerah wajib melakukan tiga hal. Pertama, memastikan ketersediaan pangan di daerah. Artinya, masyarakat memiliki stok pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Pangan yang dimaksud bisa bersumber dari pangan lokal atau pun impor. Kedua, memastikan kemampuan akses fisik dan ekonomi dari masyarakat terhadap sumber pangan secara sosial dan demografis sepanjang waktu dan di mana saja. Ketiga, memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat itu sudah memenuhi standar gizi dan kesehatan.
Ketiga kewajiban itu menjadi makin “serius” dilakoni daerah, karena ada regulasi lain yang memaksa daerah untuk menjamin terselenggaranya hak dan pelayanan dasar pangan kepada masyarakat, yaitu UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, PP No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Peraturan Menteri Pertanian No 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan.
Dengan diserahkannya urusan ketahanan pangan kepada daerah, daerah diyakini akan mampu mengembangkan diversifikasi pangan terutama ke arah pangan lokal, sehingga pangan lokal akan lebih berkembang. Impaknya, ketahanan pangan lokal akan terbentuk. Otomatis ketahanan pangan nasional pun bakal terpenuhi.
Kombinasi kewenangan
Kendati begitu, penyerahan urusan ketahanan pangan kepada daerah sejatinya juga menimbulkan dilema tersendiri. Pasalnya, pada batas tertentu, desentralisasi pangan bisa menciptakan ketidakseragaman pengelolaan pangan. Sebagai contoh, membandingkan antara Kalsel, Sulsel, dan Papua.
Menyerahkan urusan ketahanan pangan kepada Kalsel dan Sulsel, mungkin tidak akan menimbulkan masalah yang berarti. Sebab, kedua provinsi itu bisa dibilang sudah tahan pangan, khususnya sebagai produsen beras.
Kalau pun ada kelebihan produksi pangan, beras, misalnya, pemerintah provinsi akan mampu membeli kelebihan produksi, sehingga harga di pasaran tidak jatuh. Andai stok pangan di kabupaten/kota di kedua provinsi itu tidak mencukupi, pemerintah provinsi dapat menjual beras yang ada di gudang.
Tetapi, ketika dikontraskan dengan Papua, akan lain ceritanya. Warga Papua yang sekarang sudah gemar makan nasi, tetapi bukanlah daerah produsen beras, tentu akan kerepotan memenuhi kebutuhannya akan beras. Sementara, Pemerintah Provinsi Papua harus mampu menjamin terisinya perut penduduk berupa tersedianya beras.
Padahal untuk mendapatkan beras, Papua harus mendatangkannya dari daerah lain. Alhasil, Papua terbebani secara ekonomi untuk urusan beras. Beruntung Papua adalah daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat, karena ditopang dana otonomi khusus. Namun, bagaimana dengan daerah lain yang fiscal gap-nya besar? Atau, daerah yang sebagian besar APBD-nya terkuras untuk belanja pegawai. Maka, pada konteks ini, desentralisasi urusan ketahanan pangan sangat memberatkan daerah.
Kalau urusan pangan dikelola seperti itu, ketahanan pangan di tingkat nasional akan sukar terwujud. Malah, membuat persoalan baru dalam tata kelola pangan. Diprediksi, desentralisasi pangan akan membuka pintu liberalisasi. APBD dan kemampuan investasi pangan pemerintah daerah yang terbatas membuat produksi komoditas pangan di daerah tidak profitable.
Daerah yang surplus komoditas pangan utama akan cenderung membuat harga tidak menarik. Akhirnya, daerah tersebut akan mengurangi produksi pangan utama dan beralih ke komoditas yang memiliki nilai jual tinggi. Sementara, daerah yang defisit pangan bakal semakin terjepit, karena terus bergantung pada impor.
Dari pintu-pintu kecil impor di daerah itulah kapitalisme akan masuk membawa kepentingan asing, lalu menguasai pangan strategis secara nasional. Agar tidak tercipta kondisi seperti itu, pemerintah pusat harus tetap mengontrol komoditas pangan strategis, seperti beras.
Oleh karena itu, diperlukan regulasi baru sebagai turunan UU No 18 Tahun 2012 yang isinya menegaskan, wewenang menetapkan jenis dan target produksi, distribusi, serta penetapan harga komoditas pangan strategis harus berada di tangan pemerintah pusat. Diperlukan kombinasi kewenangan antara pusat dan daerah, agar terjadi keseimbangan.
Daerah boleh diberi kewenangan dalam hal mengelola komoditas pangan non-strategis, sesuai dengan potensi masing-masing. Misalnya, sayur-sayuran, garam, kelapa sawit, dan lainnya. Tetapi, khusus untuk kebijakan pangan strategis, seperti penyediaan lahan pertanian, bibit, subsidi pupuk, dan pengelolaan pertanian secara terpadu, harus tetap dalam kendali pemerintah pusat. (Moh Ilham A Hamudy)