
Proses sederhana pembuatan nata de coco dari perajin yang diserap pabrikan. foto:widi
Berselancar di Internet, Jadi Produsen Nata De Coco
Awalnya, Sriyono, 34 tahun, hanya petani tadah hujan di pelosok Ponorogo. Namun setelah bersentuhan dengan dunia internet, hidupnya pun berubah. Sriyono tak lagi mengadalkan lahan kritis yang dimilikinya tetapi menjadi produsen nata de coco. Skala produksinya memang masih kecil, namun dia yang terbesar di Ponorogo.
Volume produksi usaha milik warga Dukuh Gading RT02 RW03, Desa Sraten, Kecamatan Jenangan ini mencapai 1,3 ton per minggu. Semuanya masuk pabrik dalam bentuk nata de coco tawar.
Pabrikan kemudian memprosesnya lebih lanjut untuk dilempar ke pasaran dalam bentuk siap konsumsi. Merk-nya pun bukan lagi Sriyono atau SSW yang biasa dia digunakan, melainkan sudah made in pabrikan tersebut. Pabrikan itu nun jauh di luar Ponorogo, yaitu di Solo, Jawa Tengah.
Peluang besar tersebut, hingga sejauh ini, adalah satu-satunya yang diketahui Sriyono. Diserap pabrik memang menguntungkan, namun margin yang dia dapatkan menjadi kecil. Untuk 1,3 ton setoran nata de coco ke pabrik, uang yang dihasilkan per minggu 2,2 juta rupiah.
Ini penghasilan kotor. Belum termasuk biaya produksi, gaji 2 karyawan, ongkos angkut dari Ponorogo ke Solo. Sebenarnya pengerjaan nata de coco ini dilakukan 4 orang. Termasuk dirinya dan istri. Namun gaji dia dan istri tidak masuk hitungan.
Sriyono menghitung, biaya produksi per minggu tak kurang dari 1,2 juta. Di luar itu masing menanggung biaya lain-lain. Jadi keuntungan bersih per minggu hanya dikisaran 500-700 ribu rupiah.
Kecilnya penghasilan ini membuat Sriyono mulai mencoba melirik pasar di luar setoran ke pabrik. Ia menciptakan merk SSW nata de coco dalam bentuk siap konsumsi dan ditawarkan ke pasar-pasar. Hasilnya lumayan. Bisa menopang keuntungan. Sriyono juga menyediakan diri untuk peasanan hajatan warga sekitarnya.
“Kendala saya cukup banyak. Modal di antaranya. Semua produksi juga masih kita lakukan dengan manual. Dengan cara tradisonal. Jadi, volume juga terbatas. Permintaan pabrik sebenarnya berapapun masuk, tapi kendala peralatan jadi masalah,” kata Sriyono.

Sriyono bersama tong-tong berisi tampungan air kelapa yang diambil dari pasar-pasar di Ponorogo. foto:widi
Untuk yang produksi bukan untuk setoran pabrik, kata Sriyono, sebenarnya mendapat respon bagus dipasaran. Terutama yang rasa buah leci atau coco pandan. Volumenya selalu bertambah.
Hanya sayangnya packaging menjadi masalah. Kurang menarik, sehingga tidak mampu menyedot pelangan yang signifikan. Sementara kompetitor dipasaran sudah kelas pabrikan. “Jadi, andaikan ada bantuan begitu saya membutuhkan pelatihan untuk urusan packaging ini,” imbuh Sriyono.
Usaha nata de coco yang kini geluti Sriyono bermula dari tahun 2010. Mendapatkan info dari internet, lantas dia mencobanya. Beberapakali mencoba tidak berhasil, lantas dia ikut bekerja di usaha nata de coco milik seorang teman.
Setelah merasa bisa, tahun 2011 ia membuka sendiri usahanya. Tahun 2011 itu produksi hanya sedikit, tapi sudah bisa masuk pasar lokal. Sambil jalan, Sriyono mencari pemasaran sendiri hingga berhasil menembus pabrikan di Solo dan Magetan.
Hingga sejauh ini, di Ponorogo terdapat 3 produsen nata de coco. Kompetitor nyata bagi usaha Sriyono. Namun dia tidak khawatir, sebab volume dia yang paling besar. Selain giat mencari peluang pasar, Sriyono juga sedang mencoba membuat es nata de coco dengan ramuan gula jawa. Nata de coco dicampur dengan kelapa muda dan dijual dengan rombong-rombong es yang bisa dibawa keliling. Dia memasang istrinya untuk menangani calon bisnis baru tersebut.
Menurut Sriyono, pekerjaan membuat nata de coco ini sebenarnya pekerjaan yang susah. Harus punya ketelatenan dan ribet. Harus tahan bau asam yang menyengat. Nata de coco baru bisa dipanen setelah tujuh hari proses. Agar bisa setiap hari panen, proses produksi juga harus dilakukan setiap hari.
Mari kita simak urutan produksinya. Lebih dari 100 buah jirigen dititipkan ke para pedagang kelapa di pasar-pasar. Jirigen baru diambil setelah penuh. Waktu pengambilan 7 hari sekali. Artinya air kelapa yang dibeli dari pedagang pasar itu sudah dalam keadaan basi/asam.
Air kelapa asam kemudian direbus hingga mendidih. Lalu diberi bumbu, antara lain gula dan ZA berikut cuka. Dalam keadaan mendidih diangkat ke loyang dan dibiarkan hingga esok pagi.
Loyang berupa cetakan-cetakan seperti nampan dari plastic. Baru kemudian diberi bibit bakteri yang memang hidup dalam asam yang tinggi. Setelah itu ditutup dengan kertas koran. Penutup memakai kertas koran lantaran masih memiliki pori-pori untuk membuat bakteri nata de coco hidup. Baru tujuh hari kemudian bisa dipanen. (widi kamidi / foto:widi)

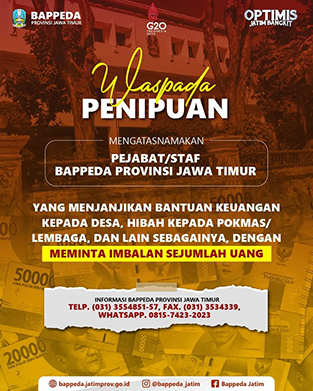

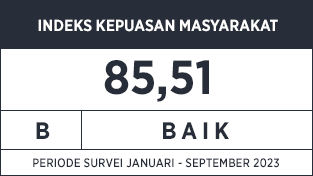









hebat….mas sriono…sayangnya alih alih memberdayakan warganya,Pemda Kab Nganjuk berencana merelokasi pedagang di timur RSUD ke tempat yang justru mematikan pendapatan pedagang, untuk perluasan parkir RSUD…yang notabene warga asli Nganjuk…..
“Jadi, andaikan ada bantuan begitu saya membutuhkan pelatihan untuk urusan packaging ini,” imbuh Sriyono.
Kiranya pemprov jatim dapat memfasilitasi pengusaha ini, karena setahu saya, setiap tahun ada program pelatihan packaging ke Jepang yang diberikan pada IKM.
Dan kiranya seleksi IKM yang mengikuti kegiatan tsb. tidak hanya dititik beratkan pada kemampuan berbahasa inggris, namun lebih pada potensi IKM tersebut untuk dapat berkembang.
Tlg mas kirim no hp yg bisa di hubungi sy perlu nata 430 ton per bln pembayaran cash