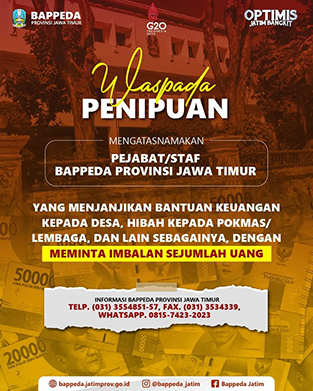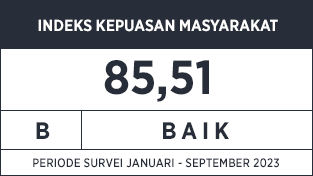Ilustrasi
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang divestasi saham perusahaan tambang mendapat kecaman karena dianggap menerapkan ”nasionalisme ekonomi”.
Ada dua pertanyaan yang timbul dari sini: apa dasar kecaman tersebut dan apakah kebijakan nasionalistis itu ada dasarnya.
Terhadap yang pertama, penerapan ”nasionalisme ekonomi” dianggap sebagai ”penyimpangan”. Mengambil jargon the invisible hand ekonom besar Inggris abad ke-18 Adam Smith, para pengecam menganggap substansi ekonomi adalah sistem pasar, yaitu sebuah sistem alokasi sumber daya paling efisien dan produktif. Pasar yang menentukan harga ketika penawaran dan permintaan tidak berimbang.
Pengaturan tak terlihat ini juga berlaku terhadap migrasi modal. Keniscayaan mencari untung membangun logika bahwa modal hanya mengalir ke sektor-sektor menguntungkan. Di luar mekanisme ini dianggap bukan kinerja sistem ekonomi ”murni”.
Agar kemurnian terjaga, impersonality (ketidakberpihakan) dan mutual benefit (saling menguntungkan) merupakan prasyarat mutlak dan harus terjamin dalam undang-undang. Logika yang dikukuhkan undang-undang ini yang menjelaskan ”universalisme” kinerja ekonomi yang ”tanpa tapal batas” mendorong migrasi aktor, modal, ataupun alat produksi dari satu ke wilayah ekonomi lain. Namun, ini hanya mungkin berlangsung dalam lingkup the sophisticated and advanced concept of the invisible hand (konsep tangan tak terlihat yang telah sangat disempurnakan), penjabarannya berbentuk business friendly policies.
Dalam perspektif inilah kebijakan ”nasionalisme” ekonomi dianggap ”penyimpangan”. Pertama, karena kebijakan itu menghadirkan aktor nonpasar: negara ”hanya” entitas politik.
Kedua, bertentangan dengan ”universalisme” kinerja ekonomi, kebijakan ini memberi ”sekat”. Kinerja ekonomi menjadi ”berwilayah” dan jadi berlawanan dengan logika impersonality, bersifat ”personal” dan ”subyektif”.
Ketiga, yang terpenting (tetapi berkaitan dengan dua poin di atas), melahirkan distorsi dalam sistem pasar murni. Distorsi inilah yang merusak dan merugikan semua pihak, termasuk negara.
Nasionalisme ekonomi
Namun, apakah ”nasionalisme ekonomi” itu buruk?
Dalam sejarah pemikirannya yang berliku—sejak Alexander Hamilto (1791) dan Friedrich List (1841) hingga awal abad ke-20— ada jejak konseptual ”nasionalisme ekonomi”, yaitu kebijakan pada tingkat nasional demi agenda sosial yang ”lebih luhur”.
Dalam Underdevelopment and Economic Nationalism in Southeast Asia (1969), Frank H Golay dan kawan-kawan menyebut ”nasionalisme ekonomi” mengacu pada sistem kebijakan nasional, dengan unit sosial negara-bangsa, untuk mencapai kepentingan nasional yang dirumuskan melalui proses politik.
Berbeda dengan ”universalisme” dan impersonality ekonomi ”murni”, ”nasionalisme ekonomi” menekankan pentingnya locus kinerja ekonomi (negara-bangsa) karena dirumuskan melalui proses politik untuk tujuan-tujuan nonekonomi.
Golay dan kawan-kawan memang menekankan faktor-faktor nonekonomi sebagai pendorong lahirnya konsep ”nasionalisme ekonomi”, terutama di negara-negara baru merdeka: efek destruktif ekonomi kolonial, kehampaan kemerdekaan politik (tanpa kontrol ekonomi) dan kepincangan struktural antara negara maju dan terbelakang. Tujuan kebijakan ”nasionalisme ekonomi” dalam lingkup negara-bangsa melampaui kesejahteraan material. Kesejahteraan material rakyat merupakan keniscayaan, melalui ”nasionalisme ekonomi”, tercapai pula rasa keadilan, keterwakilan berada bersama (inclusiveness), dan kebanggaan sosial-politik rakyat.
Tekanan pada rasa keadilan ekonomi inilah yang direfleksikan mantan Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss-Kahn di Washington, 4 April 2011. Ia memperkenalkan konsep social inclusion dan social cohesion dalam kebijakan ekonomi karena ketimpangan produk sistem ekonomi ”murni” merupakan salah satu dampak krisis global.
Maka, kebijakan ”nasionalisme ekonomi” pemerintahan Presiden SBY juga layak ditinjau dari sudut social inclusion dan social cohesion untuk mencapai tujuan nonekonomis: kepuasan sosial dan kebanggaan nasional karena ”mampu” mengontrol sumber daya sendiri.
Melalui otoritas konstitusional (Pasal 33 UUD 1945), dan dengan cara renegosiasi (bukan nasionalisasi), negara berusaha menciptakan distributive economy.
Fachry Ali Direktur Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU Indonesia)/ Harian Kompas 23 Jui 2012